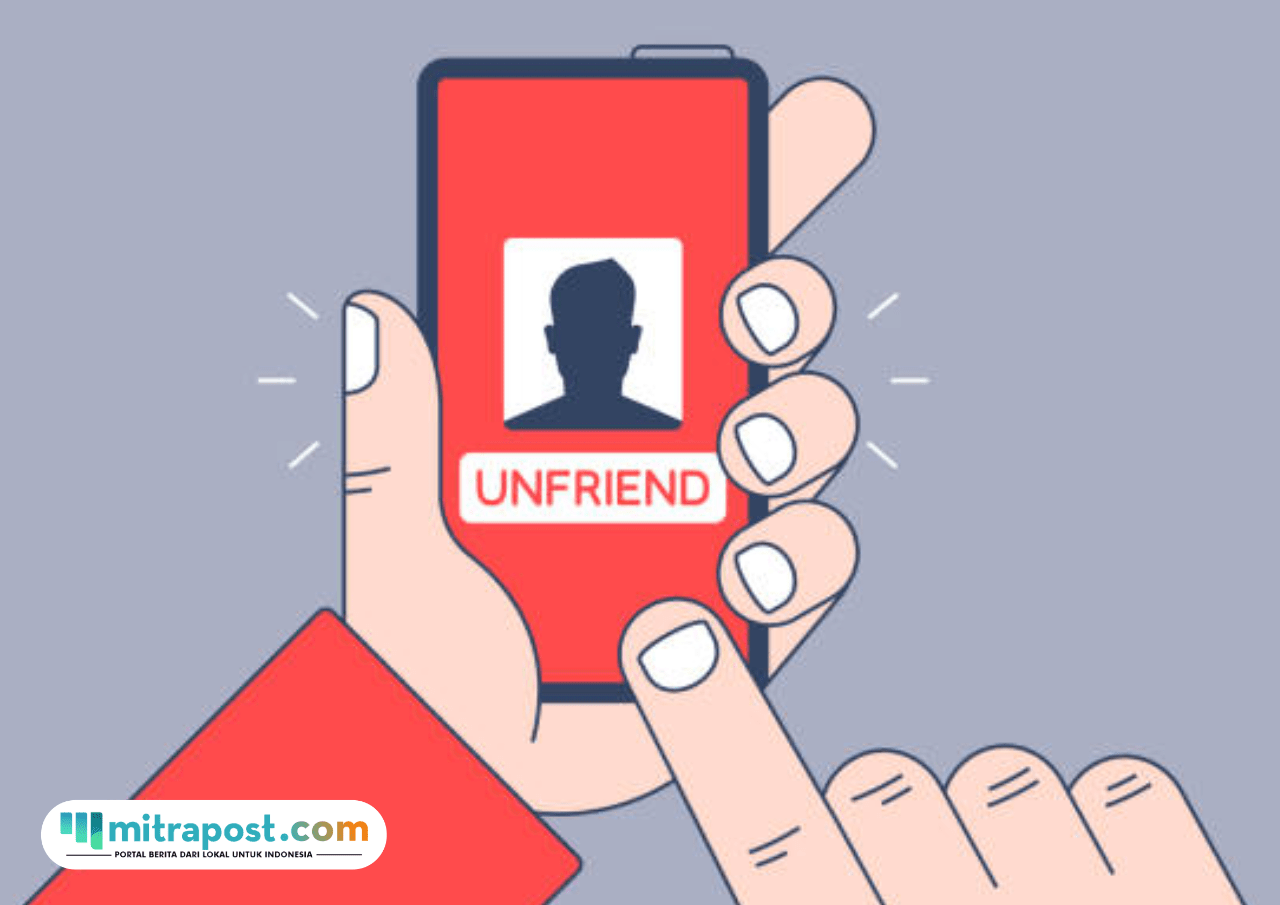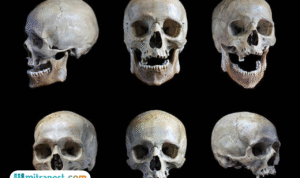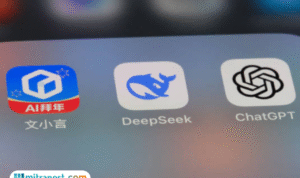Mitrapost.com – Di era media sosial saat ini, istilah cancel culture atau budaya pembatalan makin sering terdengar. Konsep ini merujuk pada tindakan kolektif untuk menghentikan dukungan terhadap seseorang atau tokoh publik yang dianggap telah melakukan kesalahan, baik secara etika, moral, maupun sosial.
Biasanya, ini terjadi setelah unggahan, pernyataan, atau tindakan mereka menuai kontroversi dan dianggap melukai perasaan publik.
Sekilas, cancel culture tampak sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Namun, seiring berkembangnya fenomena ini, muncul pertanyaan yang cukup serius: apakah cancel culture benar-benar memperkuat kesadaran sosial atau justru membatasi kebebasan berpendapat?
Di satu sisi, cancel culture dianggap sebagai alat untuk menuntut pertanggungjawaban. Masyarakat yang dulunya pasif kini memiliki kekuatan untuk menantang struktur yang tidak adil, baik dalam industri hiburan, politik, maupun institusi lainnya.
Hal ini terlihat, misalnya, dalam kasus pelecehan seksual yang terungkap berkat keberanian korban berbicara, didukung gelombang massa yang membatalkan dukungan terhadap pelaku. Dalam konteks ini, cancel culture berperan positif, yakni sebagai koreksi sosial yang tidak diberikan oleh sistem hukum formal.
Namun, di sisi lain, cancel culture kerap kali berubah menjadi vonis publik tanpa ruang dialog atau klarifikasi. Sekali seseorang ‘dicancel’, reputasinya bisa hancur dalam sekejap, terlepas dari niat, konteks, atau proses hukum yang sebenarnya.
Menurut studi yang dipublikasikan oleh Pew Research Center, hampir 49% orang dewasa di Amerika Serikat menilai cancel culture sebagai cara untuk menghukum tanpa ampun, bukan sekadar bentuk akuntabilitas.
Artinya, ada kekhawatiran bahwa budaya ini menjadikan orang takut berbicara, terutama jika opininya berseberangan dengan mayoritas.
Fenomena ini juga berdampak pada dunia akademik dan kreatif. Dosen, penulis, bahkan seniman kini sering merasa harus “berjalan di atas telur” dalam mengutarakan ide-idenya.
Di Indonesia, beberapa publik figur pun pernah menjadi sasaran cancel culture karena pernyataan yang dianggap kontroversial, padahal tidak semua pernyataan tersebut berniat menyakiti.
Akibatnya, diskusi yang sehat dan terbuka menjadi terhambat karena kekhawatiran akan reaksi publik yang impulsif.
Kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang dilindungi undang-undang, termasuk dalam Pasal 28E UUD 1945. Namun, kebebasan itu tentu harus dijalankan dengan tanggung jawab.
Dalam konteks ini, cancel culture seharusnya tidak dimaknai sebagai upaya membungkam, tetapi sebagai panggilan untuk berdiskusi lebih dalam. Menjadi warga digital yang cerdas berarti mampu membedakan antara kritik yang membangun dan serangan personal yang membungkam. (*)

Redaksi Mitrapost.com